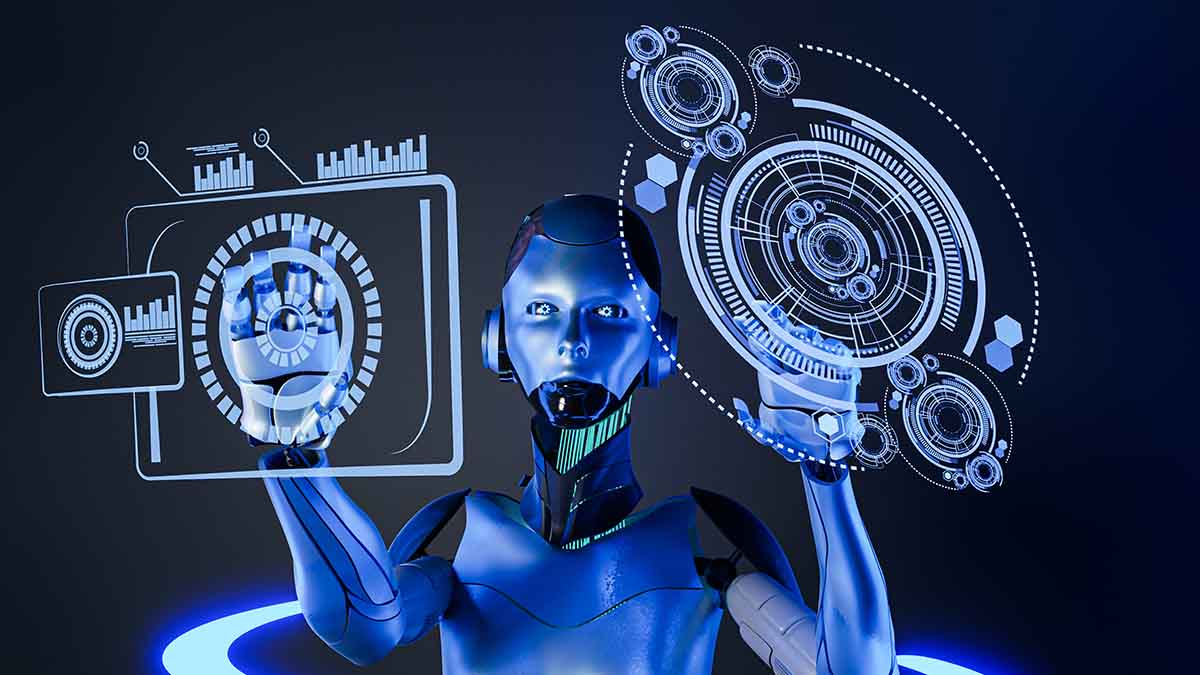TROBOS.CO | Pisau selalu bergantung pada siapa yang menggenggamnya—bisa digunakan untuk mengupas apel atau justru melukai tangan seorang pembunuh. AI pun demikian—sebuah ciptaan yang tak bersalah, namun memantulkan wajah moral dan amoral dari manusia penggunanya.
Jika AI di tangan mereka berhati jernih, ia akan menjadi alat kebaikan. Namun bila disusupi niat culas, algoritmanya bisa berubah menjadi senjata yang menusuk kemanusiaan itu sendiri.
AI lahir, pada generasi awalnya—berpacu dalam semangat objektivitas—menyingkap kebenaran, menghapus bias, dan membantu manusia mengambil keputusan berdasarkan data yang dianggap murni. Namun seiring waktu, AI pun mulai “belajar” dari manusia, dan disanalah sumber persoalannya bermula.
Persoalan menjadi nyata ketika algoritma AI, yang seharusnya objektif, justru merefleksikan dan memperkuat bias historis.
Kita menyaksikan bagaimana sistem pemeringkatan otomatis dapat menyingkirkan kelompok etnis tertentu karena model dilatih dengan data yang sarat prasangka lama.
Bahkan kategori paling mendasar seperti jenis kelamin pun dapat dipengaruhi oleh perspektif yang menginputnya: suara langit mematok gender secara fitrah hanya “pria dan wanita,” sementara dalam kerangka HAM modern, konstruksi gender dapat meluas hingga belasan kategori. Ketika kerangka ideologi yang berbeda ini masuk ke dalam desain algoritma, AI pun berpotensi memihak salah satu cara pandang dan mengabaikan yang lain, sehingga memperdalam ketimpangan representasi.
Pada saat yang sama, algoritma media sosial terus memprioritaskan konten yang memicu polarisasi—menciptakan gema yang memekakkan (echo chamber)—bukan demi kebenaran, melainkan demi durasi keterlibatan (engagement) dan keuntungan.
Kebenaran mulai dicampur kepentingan, diksi disusupi kepalsuan, hingga antar-mesin saling berdebat membawa “kebenaran” versinya sendiri. Informasi bukan lagi menjadi cahaya, melainkan kabut.
Kita hidup di zaman di mana algoritma bisa menyesatkan dengan sopan, dan kebohongan dipoles seperti kebenaran ilmiah. AI tidak lagi menjadi cermin jernih, tetapi prisma yang membiaskan realitas bergantung siapa yang menyalakan cahayanya.
Bagaimana laku kepemimpinan beradaptasi?
Spirit kearifan Jawa dan Islam—dapat menjadi penuntun moral bagi arah modernitas digital.
Kepemimpinan bukan hanya kemampuan berpikir logis, tetapi hasil dari olah rasa, olah pikir, dan olah laku. Mesin hanya mampu mengumpulkan perilaku manusia tanpa pernah benar-benar berperilaku.
Seorang pemimpin sejati, dalam pandangan Jawa, disebut pamong—ia bukan sekadar pengatur, tetapi pengasuh dan pengayom.
Pamong sejati bukan hanya ngemong rakyat, tetapi juga mampu menangkap bahana dari batin mereka—gema halus antara harapan dan duka—memeliharanya dengan welas asih, dan menuntun mereka menuju harmoni.
Kearifan kepemimpinan Jawa itu dirangkum dalam ajaran “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.” Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan.
Tiga dimensi ini bukanlah algoritma, melainkan perilaku manusia yang lahir dari rasa tanggung jawab dan cinta kasih.
AI tidak bisa menjadi tulodo karena ia tidak bisa meneladani dirinya sendiri. Ia tidak bisa mangun karso karena semangat bukanlah data, melainkan getaran hati. Dan ia tak bisa handayani, karena pengaruhnya bukan dari kasih, tapi dari kekuatan program.
Lebih jauh kepemimpinan Jawa juga mengenal gagasan “manunggaling kawula gusti”—penyatuan antara rakyat dan pemimpin dalam satu jiwa kebersamaan.
Dalam tradisi Islam, kepemimpinan Nabi dibangun di atas empat pilar moral: Shiddiq (jujur), Amanah (terpercaya), Tabligh (menyampaikan kebenaran), dan Fathonah (cerdas). Semua itu adalah perilaku, bukan logika—melainkan hasil dari keikhlasan hati, bukan hasil komputasi.
Kepemimpinan Al-Amin—yang dipercaya bahkan sebelum kenabian—lahir dari konsistensi moral, bukan dari sistem pengawasan.
Jika hari ini kita bermimpi AI bisa memimpin, kita harus ingat: amanah tidak bisa diprogram, ia hanya bisa dijaga oleh hati.
Sedangkan dalam pandangan Jawa, pemimpin ideal disebut priyayi linuwih—seseorang yang unggul dalam budi, bukan hanya dalam pangkat. Ia menjadi pamong bagi rakyatnya—menuntun tanpa menindas, melindungi tanpa membatasi.
Kepemimpinan bukanlah kekuasaan untuk memerintah, melainkan kewajiban untuk ngemong. AI tidak bisa ngemong. Ia tidak bisa ngrasani kanthi welas asih—merasakan yang dirasa rakyatnya. Ia bisa menjadi alat pamong, tetapi tidak bisa menjadi pamong itu sendiri. Pamong membutuhkan jiwa yang hidup, bukan sekedar sistem yang efisien.
Teknologi, seberapa pun canggihnya, hanyalah alat. Pisau tetaplah pisau—yang membedakan hanyalah siapa yang memegangnya.
Pemimpin sejati tidak berdiri di atas rakyatnya, melainkan tumbuh bersama mereka—ikut memikul derita, merayakan bahagia, dan menjalin nasib secara kolektif.
Kepemimpinan semacam itu lahir dari rasa manunggal, sebuah kesadaran untuk menyatu dengan denyut kehidupan rakyatnya.
Di sinilah batas ontologis antara manusia dan teknologi menjadi terang. AI, betapapun cerdas secara komputasional, tidak memiliki rasa manunggal—ia tidak dapat menjadi bagian dari rakyat, karena tidak hidup dari napas yang sama dan tidak berbagi pengalaman eksistensial manusia.
Nilai keseimbangan inilah yang sejatinya hidup dalam kebudayaan Jawa. Budaya Jawa mengenal ‘tapa’—bentuk laku batin menemukan rasa sejati—hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Demikian pula ‘tahannuts’ Nabi di Gua Hira—menyelam kejernihan batin sebelum turunnya wahyu—tulodo (teladan) memimpin keselamatan dunia dan akhirat.
Penulis: Didik P. Wicaksono. Pemerhati sosial digital dan budaya kontemporer