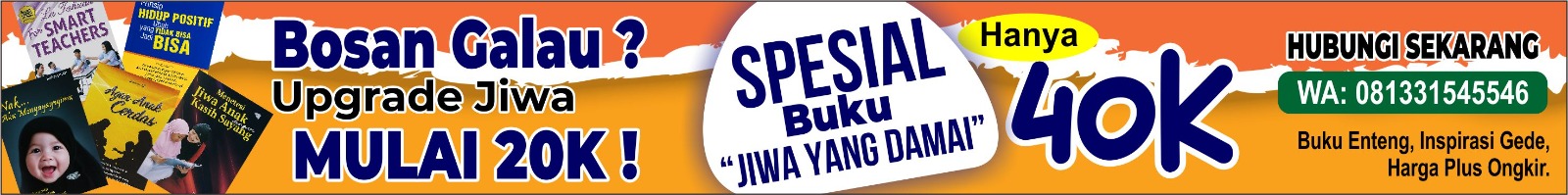Trobos.co – Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, karnaval Agustusan di Lumajang hampir selalu identik dengan parade sound horeg. Sepintas, fenomena ini terlihat sederhana: warga merakit perangkat audio dengan kekuatan suara luar biasa, dipasang di atas truk atau panggung portabel, lalu diarak di jalanan desa ketika musim karnaval tiba.
Namun jika dicermati lebih dalam, sound horeg ternyata menyimpan dinamika sosial dan kultural yang kompleks. Apa yang semula lahir dari kreativitas warga, kini menjelma menjadi industri hiburan rakyat. Biayanya pun tidak main-main, sekali sewa bisa mencapai Rp20 juta hingga Rp70 juta per malam—tergantung jenis sound system dan durasi acara.
“Apa Nikmatnya?”
Pertanyaan klasik pun muncul: apa nikmatnya mendengar musik jedag-jedug dengan volume memekakkan telinga? Mengapa warga begitu menikmatinya, bahkan rela menanggung risiko genting rumah tetangga pecah karena getaran?
Jawaban sebenarnya tidak sekadar soal suara itu sendiri. Yang lebih penting justru makna sosial dan kultural di balik gegap gempita sound horeg.
Hiburan Rakyat dan Resistensi
Stuart Hall, seorang pemikir ternama dalam kajian budaya, menyebut budaya populer bukan hanya hiburan. Ia adalah arena pertarungan antara kekuasaan dan resistensi; tempat ideologi dominan—kapitalisme dan selera kelas elit—bertemu dengan perlawanan sehari-hari rakyat biasa.
Dalam konteks ini, sound horeg bisa dibaca sebagai simbol budaya rakyat yang menantang dominasi industri hiburan arus utama. Selama bertahun-tahun, hiburan audio-visual berkualitas tinggi hanya bisa diakses lewat tiket konser mahal, klub malam eksklusif, atau acara glamor dengan aturan ketat. Bass yang menggetarkan lantai dansa dan lampu sorot yang menari biasanya hanya milik ruang-ruang elite.
Pertanyaannya: siapa yang bisa masuk ke sana? Jelas tidak semua orang.
Subversi dari Kampung
Di sinilah sound horeg hadir sebagai bentuk subversi. Ia membalik logika industri hiburan: dari yang eksklusif menjadi inklusif, dari yang mahal menjadi gotong royong, dari yang individualistik menjadi kolektif.
Semua orang bisa berjoget bersama di jalan kampung. Tidak ada dress code, tidak ada tiket, tidak ada batas sosial. Semua boleh bergembira.
Dan kegembiraan itu bukan sekadar euforia. Ia adalah bentuk pelarian, pelepasan, bahkan terapi sosial. Dalam tekanan ekonomi yang kian menghimpit dan persaingan hidup yang semakin keras, sound horeg menawarkan ruang relaksasi kolektif.
Budaya dari Bawah
Dalam teori budaya, hal ini bisa disebut sebagai praktik kultural dari bawah (bottom-up cultural practice). Warga merakit sendiri speaker-nya, membentuk komunitas, hingga menyusun acaranya. Inilah bentuk bricolage—memanfaatkan sumber daya seadanya untuk menciptakan makna baru.
Bahkan ketika volumenya terlalu keras sampai atap rumah runtuh, peristiwa itu bisa dibaca bukan sekadar gangguan, melainkan pernyataan keras: rakyat kecil juga berhak atas panggung, atas suara, dan atas ruang ekspresi.
Ambivalensi Budaya Populer
Tentu saja, sound horeg tidak tanpa masalah. Suaranya bisa sangat mengganggu, memicu konflik, bahkan menimbulkan kekacauan. Namun semua itu tidak serta-merta menghapus nilai budayanya.
Seperti halnya bentuk-bentuk budaya populer lain, ia selalu ambivalen: antara hiburan dan pelarian, antara resistensi dan komodifikasi, antara kebebasan dan keteraturan.
Dan justru di situlah letak kekuatannya.
Suara “Kami Juga Ada”
Pada akhirnya, sound horeg bukan semata soal menikmati musik keras. Ia adalah perlawanan simbolik—membuat gaduh demi didengar, berpesta di tengah ketidakpastian.
Dalam dunia yang kian seragam oleh algoritma, sponsor, dan narasi besar kapital, barangkali hanya lewat dentuman sound horeg rakyat kecil bisa dengan lantang berkata:
“Kami juga ada.”
Penulis: Agus Salim (Pengajar di STKIP Muhammadiyah Lumajang)